Jalan-jalan biasa untuk mengisi masa libur berubah menjadi perjalanan penuh tanya. Memang tidak sedalam kisah Musa dan Nabi Khaidir atau perjalanan biksu suci mencari kitab ke arah barat. Tapi saya yakin jawaban dari pertanyaan ini akan menjadi pondasi dan bekal mereka ke depan.
Tiga hari sebelum anak-anak kembali sekolah dan pesantren saya mengajak anak-anak untuk keliling Jakarta. Kali ini kami tidak naek transportasi online sebagaimana yang kerap kami lakukan. Tapi kami naik ingin mencoba sejumlah transportasi publik.
Perjalanan dimulai dengan naik angkutan umum yang akan mengantar kami ke halte transjakarta Ciledug. Pertanyaan pertama keluar dari Reyhana yang baru duduk di kelas 1 saat kami memasuki halte transjakarta. Dia bertanya kok kami tidak membeli tiket tapi hanya menempel kartu.
Saya mencoba jelaskan bahwa di dalam kartu yang kita tap itu ada sejumlah uang yang akan terpotong sejumlah kita melakukan tap atau transaksi.
“Jadi kalau di dalam kartu ada uang 10 ribu, maka akan terpotong pas kita masuk” saya coba menerangka meski gak yakin juga mereka akan langsung paham. Ketika kendaraan transjakarta menampakkan hidungnya Reyhana seakan lupa dengan soal transaksi elektronik tersebut.
Saat sedang asyik di halte CSW, Reyhan yang juga baru duduk di kelas 1 dan kembaran Reyhana bertanya, “Yah, itu garis putih-putih apa di jalan raya?”
Saya jelaskan bahwa itu Zebra Cross, tempat kita menyeberang saat di jalan raya. Jadi menyeberang itu ada tempatnya, dan pengguna kendaraan lain harus menghormati penyebrang jalan yang menggunakan Zebra Cross. Untuk pertanyaan ini saya membawanya langsung turun dan ke luar dari halte CSW dan mengajak menggunakan Zebra Cross. Kami lalu menyeberang ke arah masjid Agung Al-Azhar.
Sejatinya perjalanan akan membawa kita pada pengalaman baru yang mungkin tidak ada di tempat kita tinggal. Itu sepertinya yang dirasakan oleh Rausyan saat sedang menyusur pedestrian yang luas dan nyaman di depan gedung ASEAN ke arah masjid Agung Al-Azhar. Sambil berlari-lari dia berkata, “Enak yah buat jalan kakinya, coba ada di Tangerang”
Pertanyaan yang tidak sempat saya jawab karena dia langsung berlari ke arah masjid Al-Azhar. Setidaknya dia sudah belajar tentang komparasi.
Dari Al-Azhar kami memutuskan ke Kota Tua yang berada di Jakarta Barat. Kembali kami lanjutkan dengan Transjakarta. Tidak ada pertanyaan yang keluar dari Rausyan, Reyhan dan Reyhana saat mobil berjalan menuju Kota Tua, karena ketiganya kompak tertidur. Mengisi tenaga untuk menjelajah kota tua nantinya.
Sampai di Kota Tua kami menyempatkan makan siang dulu di KFC yang berlokasi di Kantor POS yang berhadapan dengan Museum Fatahillah. Sambil menunggu makanan komplit, Reyhan memperhatikan foto sosok tua berjenggot dan berkacamata yang ada di sejumlah sisi makanan siap saji tersebut.
“Ayah, kakek itu siapa, kok ada gambarnya?”
“Oh itu kolonel sanders, pendiri KFC”
“Oh, McD juga dia yang buat?”
“Bukan, lain lagi”
Pertanyaan terputus begitu semua menu yang kami pesan komplit.
Sesudahnya kami menjelajah Museum Fatahillah. Begitu masuk kami menuju lokasi Kamar Diponegoro. Sebelum naek ke lantai 2 tempat Pangeran Diponegoro pernah menghabiskan waktu saat ditahan oleh Belanda, kami melihat tulisan Penjara Wanita. Penjara ini ruang bawah tanah yang hanya setinggi kira-kira 1 meter saja. Jadi siapapun yang ditempatkan di penjara tersebut tidak akan bisa berdiri.
“Kok wanita dipenjara? kan, kasihan” pertanyaan pembuka dari Reyhana
“Iyah, dulu banyak pahlawan Indonesia juga dari kalangan wanita. Mereka ditangkap dan ditaro di sini”
“Kasihan yah, gak bisa berdiri. Kan pegel” tambahnya
“Ayah, aku pernah nonton film pahlawanku di pondok. Iyah banyak yang ditangkepin Belanda” Reyhan menimpali.
“Ayah, Diponegoro itu siapa” dan banyak pertanyaan lainnya mengalir selama kami berkeliling museum Fatahillah dan Museum Wayang. Pertanyaan yang sebisa mungkin saya jawab, tapi kebanyakan saya arahkan ketiganya untuk membaca keterangan diorama yang ada. Kebetulan Reyhan dan Reyhana sudah mulai lancar membaca sehingga ini menjadi ajang latihan mereka juga.
Begitulah anak-anak lewat pertanyaan mereka mencari tahu yang mengganjal di benak mereka. Itulah bentuk mereka mencari tahu. Apalagi anak-anak yang belum bisa membaca. Saya berusaha sekuat mungkin tidak membungkam usaha mereka mencari tahu. Malah bisa jadi dari banyak pertanyaan mereka saya juga ikutan mencari tahu.
Bertanya memang sangat dianjurkan selama itu merupakan pertanyaan yang jujur dan dalam rangka mencari tahu. Bertanya juga satu sikap kreatif seseorang, karena dengan bertanya akan apa yang kita lihat dan rasakan bisa menghasilkan solusi.
Tapi bertanya juga bisa menjadi masalah bagi diri sendiri jika itu motifnya hanya untuk bermain-main atau membuat kesal mereka yang ditanya, sebagaimana Bani Israil yang yang diperintahkan untuk menyembelih sapi, tapi selalu banyak bertanya tentang kriteria sapi yang justru menyulitkan mereka.
Maka sapi yang mulanya bersifat umum, menjadi semakin spesifik akibat terus ditanyakan: Sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, kuning tua warnanaya lagi menyenangkan orang yang memandangnya, belum pernah dipakai untuk membajak tanah , tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak cacat dan tidak ada belangnya. Akhirnya spesifikasi semacam inilah yang justru semakin menyulitkan mereka.
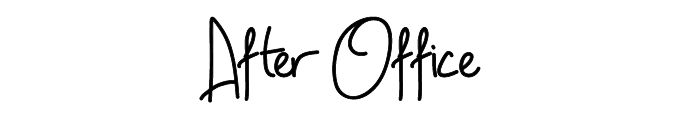











Tidak ada komentar